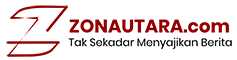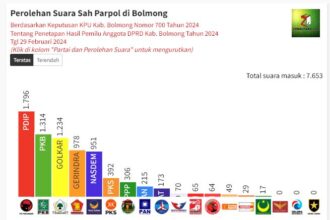CATATAN REDAKSI
Senin siang, 1 September 2025. Panas terik menggantung di langit Manado. Jalan di depan Gedung DPRD Sulawesi Utara yang terletak di Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, dipadati ribuan mahasiswa, buruh, dan warga yang menyatu dalam satu barisan panjang.
Spanduk terentang, suara toa bersahutan, dan semangat kolektif memantul dari dinding gedung parlemen daerah.
Namun, di antara lantang pekik tuntutan, ada seruan lain yang tak kalah nyaring: “awas intel!”.
Seruan itu terdengar berulang, seperti gema yang berpindah dari satu sisi barisan ke sisi lain. Kepala-kepala menoleh, mata-mata menyipit, mencari sosok asing di tengah kerumunan.
Tidak ada yang pasti siapa yang dimaksud. Tapi pekik itu cukup untuk membuat seluruh massa kembali siaga.
Bagi sebagian orang, teriakan itu hanyalah paranoia atau curiga yang berlebihan. Tetapi bagi mereka yang tumbuh dalam tradisi demonstrasi di negeri ini, “awas intel” adalah peringatan. Sebuah alarm yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Jejak panjang kecurigaan
Kata “intel” telah lama hidup dalam imajinasi publik Indonesia. Ia bukan sekadar sebutan untuk aparat intelijen yang bekerja di balik layar.
Dalam dunia aktivisme, “intel” identik dengan sosok misterius: berpakaian sipil, hadir tanpa identitas, dan sering muncul di saat genting.
Sejarah aksi massa di negeri ini menyimpan banyak kisah tentang penyusup. Ada yang sekadar mengamati, mencatat, dan pergi diam-diam.
Namun tak jarang, ada pula yang dituding sebagai provokator—menyalakan api kerusuhan, lalu menghilang begitu saja.
Itulah mengapa, setiap kali massa turun ke jalan, seruan “awas intel” menjadi mantra pengingat: jangan lengah, jangan pecah, jangan biarkan suara rakyat dibajak.
Agustus 2025: Saat damai berubah ricuh
Narasi ini menemukan cerminnya beberapa hari sebelum aksi Manado, ketika gelombang protes besar-besaran mengguncang Jakarta dan sejumlah kota besar lain di Indonesia.
Akhir Agustus 2025, ribuan buruh, mahasiswa, dan kelompok ojek online memenuhi jalan-jalan di ibu kota.
Tuntutannya jelas: penolakan terhadap kebijakan pemerintah, seperti tunjangan besar anggota parlemen, menolak kenaikan harga kebutuhan pokok dan menghapus kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap menindas.
Dari pagi hingga siang, aksi itu berjalan damai. Orasi bergulir rapi, barisan tertib, spanduk terbentang.
Namun menjelang sore, suasana berubah drastis. Sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba melempar benda keras ke arah pagar DPR. Ada yang mencoret dinding, merusak fasilitas, hingga membakar atribut.
Polisi merespons dengan gas air mata dan tembakan peluru karet. Jalan tol Senayan sempat lumpuh karena massa memblokade jalur.
Tragedi pun tak terhindarkan. Sejumlah orang tewas termasuk seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang meninggal akibat tertabrak kendaraan polisi, puluhan lainnya luka-luka, bahkan ada yang dilaporkan hilang.
Aksi yang awalnya damai seketika berubah menjadi potret ricuh yang menghiasi layar televisi dan media sosial.
Pasca kejadian, polisi menyebut ada “penyusup” yang memicu kerusuhan. Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, juga menuding adanya “penumpang gelap” yang bukan bagian dari gerakan.
Pengamat melihat pola terstruktur, seolah kerusuhan itu bukan spontanitas, melainkan skenario.
Kronologi ini semakin menegaskan bahwa kekhawatiran massa di Manado bukan tanpa dasar. Bahwa seruan “awas intel” adalah wujud memori kolektif, lahir dari pengalaman nyata, bukan sekadar ketakutan kosong.
Intel: Wajah yang selalu abu-abu
Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan “intel”? Secara formal, mereka adalah aparat yang bertugas memantau dinamika sosial, mencatat peristiwa, dan mengantisipasi potensi konflik.
Namun di mata publik, definisi itu kabur. “Intel” lebih sering diimajinasikan sebagai sosok asing yang menyusup, mengawasi, bahkan memprovokasi.
Apakah intel yang memprovokasi? Tidak ada jawaban pasti. Tetapi kecurigaan sudah terlanjur melekat. Setiap gerakan massa seakan hidup bersama bayang-bayang asing yang bisa muncul kapan saja.
Lebih dari sekadar seruan
Di Manado, seruan “awas intel” bukan sekadar kecurigaan yang berlebihan. Ia adalah refleks kolektif, sebuah mekanisme pertahanan diri.
Sebuah peringatan agar barisan tetap solid, agar setiap orang saling menjaga, agar perjuangan tidak dibelokkan.
Namun lebih jauh, ia juga cermin dari rapuhnya kepercayaan publik kepada negara. Selama masih ada dugaan penyusupan, selama provokasi masih mungkin muncul dari mereka yang tak jelas identitasnya, maka teriakan itu akan terus bergema.
“Awas intel” bukan hanya tentang orang mencurigakan di tengah massa. Ia adalah simbol dari kegelisahan yang lebih dalam: bahwa suara rakyat bisa hilang arah bila bayang-bayang gelap dibiarkan terus menghantui jalanan.