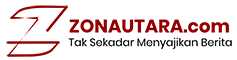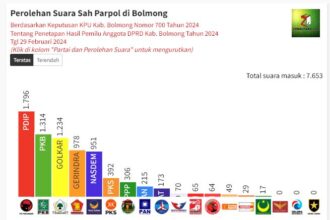Desember 2024 seharusnya menjadi bulan penuh sukacita bagi Rina Walangitan (55), warga Kelurahan Toulour, Kecamatan Tondano Timur di tepian Danau Tondano. Namun, Natal tahun itu berbanding terbalik dengan harapannya. Suara Rina terdengar serak bergetar saat menceritakan malam pilu ketika air danau merenggut rumahnya.
Sepulang beraktivitas pada malam 24 Desember, ia terkejut mendapati lantai rumahnya sudah terendam banjir setinggi lutut. Barang-barang berharga terpaksa ditinggalkan begitu saja; sambil menenangkan diri, ia hanya sempat menyelamatkan beberapa pakaian dan perabot yang masih bisa digunakan. Malam semakin larut, air terus meninggi hingga mencapai leher Rina yang bertubuh sekitar 148 cm. Bermodalkan perahu pinjaman tetangga, ia bertahan di dalam rumah yang sudah berubah menjadi “akuarium” banjir kala itu. Dua minggu kemudian barulah air mulai surut, tetapi rumah Rina yang persis di bibir danau tetap tergenang.
“Tak ada rasa bahagia yang hadir kala Natal tahun lalu, semua terjadi begitu saja. Perabotan yang tak terselamatkan, duka itu masih terasa hingga hari ini. Capek sekali, baru saja tahun lalu, kini terjadi lagi,” ucap Rina lirih, mengenang Natalnya yang kelam.
Lima bulan berselang, memasuki Mei 2025, banjir kembali merendam rumahnya dengan ketinggian serupa. Rina yang sehari-hari bekerja sebagai pemasang umpan di perahu nelayan kehilangan mata pencaharian. Sejak desanya terendam, tak ada lagi perahu yang bisa melaut, penghasilannya pun lenyap.
“Setahun terakhir, tak ada lagi tanah kering di pekarangan,” keluhnya, seraya melontarkan kemarahan karena bencana ini bukan semata-mata ulah alam, melainkan akibat kelalaian manusia.
Banjir luapan Danau Tondano kali ini di luar dugaan – yang terbesar sepanjang hidupnya. Dengan putus asa, Rina menyalahkan pemangku kepentingan yang tak sigap mengantisipasi kenaikan debit air di bulan Mei 2025.
“Juni 2024 rumah saya yang paling pertama terendam banjir dan Juni 2025 rumah saya yang paling terakhir surut. Coba kalau diantisipasi sejak Mei, tidak bakalan ada kejadian seperti ini, bodoh sekali mereka (pemerintah) itu,” ungkapnya geram.
Hingga pertengahan Juni 2025, air di rumah Rina masih setinggi perut orang dewasa. Natal silam tak menyisakan sukacita bagi Rina – hanya lumpur dan pilu yang membekas di ingatannya.
Rina tidak sendiri. Di berbagai penjuru sekitar danau, ratusan keluarga senasib dengannya. Misi Wensen (34), warga Desa Tounelet, Kecamatan Kakas, menceritakan bagaimana rumahnya yang baru setahun ditempati – bangunan baru bantuan pemerintah – ikut terendam banjir. Padahal, ia sudah membangun rumah panggung lebih tinggi dari patokan banjir tahun lalu sesuai saran orang dinas, namun tahun ini air bah melampaui segalanya.

“Kali ini jauh lebih parah, bahkan rumah baru pun terendam. Tahun lalu memang banjir, tapi tidak separah ini,” ujarnya cemas.
Aktivitas sehari-hari di desanya lumpuh. Warga harus berperahu kecil untuk bepergian. “Ini sudah hampir dua bulan banjir baru surut,” kata Misi, seraya menghitung lebih dari 200 kepala keluarga di Tounelet yang turut terdampak banjir kali ini. Ia khawatir, “Ke depan bagaimana kalau banjir lebih tinggi dari ini?” – sebuah pertanyaan getir yang terngiang di benak banyak warga.
Flanda Sinaulan (47), tetangga Misi di Kakas, juga mengaku banjir kali ini jauh melampaui banjir-banjir sebelumnya. Akibat cuaca dingin dan genangan yang bertahan berminggu-minggu, tiga ekor anjing peliharaannya mati kedinginan. “Kami terbiasa menghadapi banjir, tapi skala dan durasinya kali ini benar-benar luar biasa,” keluhnya. Suami Flanda yang sehari-hari mencari ikan di Danau Tondano tak bisa turun selama banjir, membuat pemasukan keluarga hilang sama sekali.
Di desa yang sama, Stevi Badu (48) menyoroti krisis air bersih pascabanjir panjang ini. “Di desa kami, hanya tersisa satu rumah yang tidak terendam – rumah milik Royke Tuniwang – dan kami semua mengambil air bersih dari sana,” ungkapnya. Untuk makan sehari-hari, warga Tounelet terpaksa bergantung pada 11 posko bantuan yang didirikan pemerintah dan relawan. Stevi khawatir jika tidak ada penanganan serius, dampak banjir akan kian besar.
“Dulu banjir hanya di sekitar danau, tapi sekarang sudah meluas – sekitar 80% wilayah desa terdampak,” katanya, miris melihat air yang tiap tahun menjangkau wilayah lebih luas.
Kondisi serupa dialami warga di kecamatan lain. Noldy (60), warga Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, bercerita bahwa sungai di kampungnya dulu sedalam 6 meter, kini dangkal tersumbat sedimen akibat erosi dan penebangan hutan.
“Akibat banjir, selama dua minggu kami terpaksa beraktivitas di atas air. Bahkan WC di rumah tidak bisa dipakai, jadi harus pakai WC di Alfamart,” keluh Noldy dengan getir. Istrinya, Linda Tumampas, menambahkan banjir besar mulai terjadi sejak akhir April 2025 dan baru surut 10 Juni.
“Ini parahnya sebanding dengan banjir besar tahun 1980-an. Sebagian besar warga di sini pakai sumur bor, tapi sekarang airnya tak bisa dipakai karena tercemar. Air bersih jadi sangat sulit didapat. Kami sudah rasakan dampaknya – beberapa warga kena diare dan gatal-gatal,” ujarnya, menggambarkan dampak kesehatan akibat air danau yang kotor.

Memori kelam banjir berulang?
Banjir Danau Tondano pada 2025 ini memang membangkitkan memori kelam empat dekade silam. Menurut sejarawan Roger Allan Cristian Kembuan, M.A. dari Universitas Sam Ratulangi, banjir besar di Danau Tondano cenderung berulang tiap sekitar 40 tahun. Warga kerap menyandingkan banjir tahun ini dengan banjir dahsyat era 1980-an – mengindikasikan semacam siklus periodik.
Catatan sejarah pun menunjukkan banjir besar pernah terjadi di pertengahan abad ke-20. Siklus ini menegaskan bahwa sejak dulu Danau Tondano memang menyimpan ancaman banjir berkala, namun dampaknya kini jauh lebih luas akibat ulah manusia. Luapan tahun ini melumpuhkan banyak area yang sebelumnya tak pernah kena banjir. Air menyebar dari Kecamatan Tondano Timur hingga Remboken dan Kakas. Bahkan desa-desa yang dulu aman kini ikut tenggelam.

“Banjir di Tondano tahun ini merupakan yang paling parah dalam lima tahun terakhir,” ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, seraya mencatat periode hujan lebat 21 April hingga 1 Mei 2025 yang memicu luapan danau. Sedikitnya lima kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Kakas, Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Tondano Timur, Kecamatan Eris dan Kecamatan Remboken.
Menurut data BNPB, sebanyak 2.757 kepala keluarga atau sekitar 7.330 jiwa mengalami dampak banjir ini; 1.313 jiwa di antaranya terpaksa mengungsi ke pos-pos penampungan maupun ke rumah kerabat. Banjir yang merendam permukiman warga hingga hampir dua bulan lamanya ini menyebabkan 1.889 unit rumah terdampak dan 4 sekolah rusak. Ratusan bangunan lain seperti gereja dan fasilitas umum di sekitar danau juga terdampak banjir.
Bagi masyarakat sekitar, bencana ini adalah alarm bahwa ada yang tidak beres dengan danau kebanggaan mereka. Ketabahan warga menghadapi banjir kini dibarengi pertanyaan: mengapa Danau Tondano yang dulu membawa berkah, sekarang justru menjadi ancaman?

Danau Tondano merupakan danau vulkanik seluas sekitar 4.000 hektare – terluas di Sulawesi Utara – yang terletak di jantung Tanah Minahasa, diapit oleh perbukitan dan gunung-gunung: Lembean, Kaweng, Masarang, serta Bukit Tampusu. Dulu, airnya jernih, panoramanya elok memikat wisatawan, dan kekayaan ikannya menyokong penghidupan warga melalui perikanan air tawar serta irigasi pertanian. Hutan lebat di pegunungan sekitar turut menjaga keseimbangan ekologis dan menjadi sabuk hijau alami bagi daerah tangkapan air.
Secara historis maupun budaya, Tondano dan danaunya tak terpisahkan dari identitas lokal. Istilah “Tondano” sendiri berasal dari bahasa daerah Minahasa: tou (orang) + (e)n (penanda genitif) + rano (air) – secara harfiah berarti “orang air”. Sejak masa lampau, orang Tondano dikenal sebagai komunitas yang hidup di atas atau dekat air, sesuai julukan tersebut.
Roger Kembuan mengungkap, catatan penjelajah Eropa abad ke-17 menyebut penduduk Tondano kala itu tinggal di rumah-rumah panggung di atas permukaan danau. Litografi tua dan laporan Gubernur VOC Robertus Padtbrugge (1679) bahkan menggambarkan perkampungan Tondano lama berada di perairan – tepatnya di lokasi yang kini dikenal sebagai Benteng Moraya – sehingga Belanda dulu harus menggunakan perahu saat hendak menyerang Tondano.
Seusai Perang Tondano awal 1800-an, pemukiman lama di atas air itu ditinggalkan. Ketika Inggris mengambil alih dari Belanda pada 1811–1816, mereka mereklamasi lahan dan menurunkan tinggi muka danau dengan memperdalam kanal Tonsea Lama (satu-satunya sungai outlet Danau Tondano) demi mencetak lahan persawahan dan membangun kota Tondano yang baru.
Kota Tondano modern pun lahir di daratan hasil drainase tersebut. Namun, di awal 1900-an sebagian area masih rawa sehingga rumah-rumah yang dibangun umumnya berupa rumah panggung tinggi. Masyarakat kala itu tetap menggunakan perahu di beberapa lokasi pemukiman, karena air danau masih rutin naik pada waktu-waktu tertentu.

“Pertama dibangun, rumah-rumah masih bertiang karena di waktu tertentu airnya akan naik. Dulu orang Tondano di awal abad 20 masih menggunakan perahu untuk menyusuri kota,” ujar Roger, memaparkan bagaimana leluhur orang Tondano hidup berdampingan dengan danau dan pasang surutnya air.
Perubahan besar terjadi pada dekade 1980–1990-an, ketika orang mulai meninggalkan rumah panggung dan beralih mendirikan rumah tapak di tanah rendah. “Dulu kalau ke Minahasa, rumahnya tinggi semua,” kenang Roger, “perubahan ke rumah tapak terjadi di era 1980-90-an”.

Labirin persoalan yang rumit
Akan tetapi, kemegahan Danau Tondano di masa lalu terancam tinggal kenangan. Degradasi lingkungan telah mengubah wajah danau ini secara drastis. Kedalaman danau menyusut tajam – dari sekitar 40 meter pada tahun 1934 menjadi hanya 13–15 meter pada tahun 2023. Penyusutan lebih dari dua pertiga ini mencerminkan parahnya pendangkalan akibat sedimentasi.
Studi batimetri terbaru yang dilakukan oleh tim Joyce Christian Kumaat, M.Sc. dari Universitas Negeri Manado mengonfirmasi kondisi tersebut: kedalaman rata-rata Danau Tondano kini hanya 13,0 meter dengan volume air sekitar 590,6 juta m³. Luas permukaan danau pun terus menyempit.
Awal abad ke-20, Danau Tondano membentang sekitar 5.000 hektare; kini luas efektifnya tinggal ±4.278 hektare akibat pendangkalan dan okupasi lahan di tepian danau. Tren penyusutan ini jelas mengkhawatirkan.
Pendangkalan (sedimentasi) merupakan salah satu persoalan utama Danau Tondano. Erosi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano yang bermuara ke danau telah mengendapkan jutaan meter kubik lumpur di dasar danau selama puluhan tahun. Kerusakan hutan di wilayah hulu akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan mempercepat laju erosi tersebut.
Data tahun 2001 menunjukkan tutupan hutan di DAS Tondano tinggal 8,75% saja – angka yang sangat memprihatinkan. Studi lain mencatat laju erosi rata-rata di hulu Danau Tondano meningkat 61,56% hanya dalam kurun 2011–2014. Artinya, sedimen yang masuk ke danau kian banyak setiap tahun, mengendap dan mendangkalkan danau dari waktu ke waktu.

Selain sedimentasi, Danau Tondano menghadapi pencemaran air serius yang berujung pada eutrofikasi (ledakan kesuburan alga/tumbuhan air akibat nutrisi berlebih). Limbah padat maupun cair – mulai dari sampah rumah tangga, sisa deterjen, hingga kotoran restoran apung – banyak dibuang langsung ke danau atau melalui sungai-sungai yang bermuara ke situ.
Diperkirakan rata-rata 2 hingga 5 truk muatan limbah, sampah, dan gulma air memasuki Danau Tondano setiap hari. Minimnya fasilitas sanitasi (seperti septic tank) membuat limbah domestik sering langsung meresap ke tanah dan lari ke danau. Peningkatan kandungan nutrien (fosfat, nitrat) dari polusi ini memicu eutrofikasi yang ditandai tumbuh suburnya gulma air eceng gondok (Eichhornia crassipes).
Aktivitas pertanian dan peternakan ikan di sekitar danau turut memperparah pencemaran. Penggunaan pupuk kimia di lahan pertanian sekitar tanpa pengelolaan memadai menyebabkan limpasan nutrisi (fosfor, nitrogen) masuk ke perairan, mempercepat pertumbuhan alga dan tumbuhan air. Selain itu, ribuan Keramba Jaring Apung (KJA) untuk budidaya ikan memenuhi perairan Tondano.
Pakan ikan berlebih dan kotoran hasil budidaya menambah beban bahan organik di ekosistem danau. Pada tahun 2010 saja, terdapat sekitar 9.833 unit KJA yang diperkirakan menghasilkan limbah organik 2.915 ton per tahun, plus nitrogen 138,8 ton dan fosfor 29 ton per tahun ke Danau Tondano. Kini jumlah KJA diduga melampaui 10.000 unit, membebani danau dengan polutan organik dan nutrien yang memicu eutrofikasi, sedimentasi, serta penurunan kadar oksigen.
Pertumbuhan keramba ikan ini berlangsung nyaris tak terkendali. Dalam riset di wilayah timur Danau Tondano, Joyce Kumaat menemukan jumlah KJA meningkat 7,2% antara 2003–2012, lalu melonjak hingga 75% pada 2012–2021. Lonjakan ini ditengarai akibat ketiadaan regulasi tegas yang mengatur pemanfaatan danau, sehingga keramba dibangun secara serampangan tanpa kendali.

Ledakan eceng gondok adalah persoalan lain yang mencolok di Danau Tondano. Gulma air ini dulunya tidak ada di danau – diduga merupakan spesies pendatang (invasif). Denny Taroreh, aktivis dari Tamangbae Lingkungan, mengisahkan sebuah teori asal-usul eceng gondok di Tondano. Konon, pada suatu proyek pengerukan danau di masa lalu, alat berat didatangkan dari luar daerah dan tanpa sengaja membawa benih eceng gondok yang tertinggal di mesin. Versi cerita lain menyebut gulma ini dibawa seseorang entah kapan, namun yang pasti sejak kemunculannya eceng gondok berkembang biak sangat cepat dan kini menutupi area danau yang luas.
Denny mengungkapkan penyebaran eceng gondok sangat dipengaruhi arah angin – ketika angin bertiup ke timur, gulma terdorong menumpuk ke sisi timur danau, lalu berpindah arah sesuai musim. Hingga kini, data mengenai total luasan sebaran eceng gondok hingga kini belum terdokumentasi dengan baik.
“Data luasan eceng gondok sangat penting agar bisa diketahui seberapa banyak dan luas penyebarannya. Dengan data tersebut, barulah bisa ditentukan cara penanganan yang tepat,” kata Denny.
Padahal, berbagai penelitian mencatat dampak gulma air ini terhadap ekosistem dan banjir. Pertumbuhan eceng gondok yang tak terkendali dapat menyebabkan tersumbatnya aliran sungai, mempercepat pendangkalan perairan, dan meningkatkan potensi banjir. Sebuah studi (Desky et al., 2020) bahkan mengungkap bahwa eceng gondok dapat menyerap atau menguapkan air permukaan hingga 4 kali lipat lebih banyak; selain itu tumbuhan ini mempercepat sedimentasi ekosistem perairan dan menutup aliran keluar-masuk air di danau maupun sungai, sehingga meningkatkan risiko banjir di sekitarnya.

Belakangan, upaya penanganan gulma ini mulai menunjukkan progres, meski jalannya tak mudah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa, Vicky Kaloh, mengklaim pihaknya telah berhasil mengangkat lebih dari separuh populasi eceng gondok di Danau Tondano. Pembersihan massal ini buah kerja sama DLH dengan Kodim 1302 Minahasa (TNI AD) yang dipusatkan di tiga titik: Tonsaru, Remboken, dan Kakas.
“Dari total 294 hektare tutupan eceng gondok, sudah lebih dari setengah yang diangkat. Bisa dicek,” ucap Vicky pada Selasa (19/08/2025), sembari menunjukkan hamparan danau yang mulai terbuka.
DLH sendiri memiliki tupoksi terkait Danau Tondano di tiga bidang: penataan tata lingkungan (bersama instansi lain seperti PUPR soal RDTR Kawasan Danau), pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sampah. Dalam hal pengendalian pencemaran, fokus DLH adalah pengujian kualitas air dan pengendalian eceng gondok. Sebagian kecil eceng gondok dimanfaatkan menjadi pupuk dan kerajinan. “Meski hanya sebagian kecil saja,” tegas Vicky.
Upaya pembersihan eceng gondok selama ini kerap terbentur masalah konsistensi dan partisipasi. Linda Tumampas, warga Kelurahan Tuutu, Tondano Barat menyoroti program pembersihan eceng gondok sebelumnya yang tidak berkelanjutan. Ia mempertanyakan mengapa tenaga honorer dari instansi pemerintah mendapat gaji tinggi, sementara masyarakat lokal hanya diminta kerja bakti dengan imbalan minim.
Ada ketimpangan antara kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi riil warga. Upah yang ditawarkan untuk memberantas eceng gondok saat itu hanya Rp50 ribu per hari – sangat rendah dibanding pendapatan harian rata-rata penduduk.
“Eceng gondok ini tumbuh sangat cepat, tapi bayaran untuk bersihkan danau cuma segitu, siapa yang mau?” lanjutnya mengungkap alasan warga enggan terlibat.

Tak hanya masalah ekologi, Danau Tondano juga menghadapi persoalan tata ruang dan hukum. Penyempitan luas danau tak lepas dari okupasi lahan di sekelilingnya. Lahan yang seharusnya menjadi sempadan danau (minimal 50 meter dari garis pasang tertinggi) justru dijadikan permukiman, kebun, bahkan obyek wisata. Banyak rumah warga berdiri persis di garis air, melanggar aturan sempadan. Pemerintah daerah kesulitan menertibkan – apalagi sebagian lahan di bibir danau sudah bersertifikat hak milik.
“Daerah sempadan itu kan sebenarnya tidak bisa ditempati. Persoalannya, pemukiman-pemukiman itu sudah ada sejak lama dan telah memiliki sertifikat tanah,” ujar Camat Remboken, Vecky Sengke mengakui dilema penegakan aturan.
Menurut Vecky, lima desa di Kecamatan Remboken terdampak banjir tahun ini dengan durasi hingga kurang-lebih dua bulan. Hal itu diperparah oleh fakta banyak warga yang tinggal terlampau dekat dengan danau – bahkan di area langganan banjir sejak dulu. Meski sempadan secara hukum tak boleh dihuni.
Kepala Satker Operasi & Pemeliharaan SDA Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Ronald Parengkuan, turut mengakui hal ini sebagai tantangan besar. “Ini sudah rahasia umum. Yang saya dengar, badan danau itu sudah punya sertifikat, dan hampir di sepanjang danau,” ucap Ronald saat ditemui di kantornya Kamis (21/8/2025).
Ketika area danau bahkan “dimiliki” secara pribadi, penataan ulang menjadi kompleks. Lemahnya zonasi dan rendahnya kapasitas penegakan hukum selama ini memperparah keadaan. Di sisi lain, anggaran daerah yang terbatas membuat pemerintah kesulitan membebaskan lahan atau membangun infrastruktur penyangga lingkungan di sekitar danau.
Semua persoalan di atas menjadikan Danau Tondano ibarat labirin masalah lingkungan yang kompleks. Terjadi trade-off antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan kelestarian lingkungan jangka panjang. Budidaya ikan dengan KJA serta keberadaan restoran terapung di danau, misalnya, merupakan sumber mata pencaharian penting bagi warga. Namun aktivitas ekonomi itu juga menjadi kontributor utama pencemaran dan pendangkalan danau.

“Persoalan Danau Tondano menjadi kompleks karena banyak kepentingan di dalamnya. Banyak pihak ingin ikut mengatasi masalah, namun karena terlalu banyak, tak satu pun yang berhasil hingga kini,” kata Denny Taroreh menggambarkan koordinasi yang amburadul selama ini.
Linda Tumampas seperti warga lainnya yang hidup di tepi danau merasakan langsung dilema tersebut. Ia dan suaminya selama ini menggantungkan hidup dari menangkap ikan dan berjualan di warung tepi danau, namun kini mereka dihadapkan pada pilihan sulit: bertahan dengan sumber nafkah yang justru mencemari danau atau meninggalkannya demi kelestarian lingkungan.
“Kami ini masyarakat kecil hanya ikut program pemerintah saja. Tapi tolonglah, kalau suruh kami bersihkan danau, berikan juga ganti rugi yang layak. Jangan hanya suruh kerja bakti terus,” pintanya, berharap ada kebijakan yang lebih adil bagi warga.
Di tengah kompleksitas persoalan Danau Tondano, asa untuk pemulihan tetap ada. Berbagai pihak mulai menyadari urgensi bertindak meskipun tantangannya besar. Saat ini, fokus utama pemangku kepentingan adalah mitigasi dampak banjir yang baru saja terjadi. Warga seperti Misi Wensen dan Flanda Sinaulan sudah berupaya beradaptasi – mereka meninggikan fondasi rumah setelah banjir sebelumnya – namun banjir tahun ini ternyata jauh melampaui perkiraan mereka. Langkah adaptasi mandiri ini menunjukkan masyarakat berusaha hidup berdampingan dengan risiko banjir, sembari menunggu solusi permanen dari pemerintah.

Dari sisi hulu, pengelola PLTA Tanggari mengambil langkah darurat mengendalikan tinggi air danau. Saat Rakor Penanganan Banjir di Minahasa pada 12 Juni 2025, Manajer PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Minahasa (PLTA Tanggari), Agus, menyatakan bahwa sejak Mei 2025, pintu air (radial gate) waduk PLTA dibuka secara berkala untuk mengurangi volume air dan sedimen di danau. Langkah ini membuat aliran keluar danau membawa banyak sampah dan lumpur, tetapi dianggap perlu agar tekanan air di Danau Tondano maupun di bendungan PLTA tidak berlebihan. Upaya teknis tersebut adalah bagian dari manajemen aliran sungai, walau sifatnya sementara dan belum menyentuh akar masalah di danau.
Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga mulai digencarkan, meski dirasa masih kurang. Warga mempertanyakan minimnya penyuluhan langsung; pengetahuan tentang konservasi danau justru lebih banyak mereka dapat dari media massa dan media sosial ketimbang dari program resmi pemerintah. Ini menandakan perlunya komunikasi dua arah yang lebih intens antara pemerintah dan komunitas lokal dalam setiap rencana aksi penyelamatan Danau Tondano.
“Masyarakat harus terlibat. Dan kalau memang itu sempadan, sebaiknya jangan bangun rumah di situ. Masih banyak sampah juga di danau. Kita harus mencintai danau ini,” imbau Ronald Parengkuan dari BWS Sulawesi I, mengajak warga untuk berkolaborasi menjaga danau.

Upaya mencari solusi penyelamatan
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan banjir di Tondano membutuhkan solusi permanen agar bencana serupa tak terulang di masa mendatang. Ia menyebut dalam tiga tahun terakhir intensitas bencana di Sulawesi Utara meningkat akibat perubahan iklim dan curah hujan tinggi. Khusus di Tondano, banjir dipicu kombinasi hujan deras yang menaikkan air danau, pendangkalan danau, serta tersumbatnya aliran sungai oleh sedimen dan sampah.
“Masalah ini tidak bisa ditangani satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi jangka panjang,” tegas Suharyanto.
Salah satu solusi jangka panjang yang diusulkan BNPB adalah relokasi masyarakat yang tinggal di area rawan sekitar danau. Jika skema relokasi ditempuh, pemerintah daerah akan menyiapkan lahannya, sedangkan BNPB akan membangun rumah bagi warga yang direlokasi. Tiga opsi ditawarkan kepada warga terdampak banjir Danau Tondano: pertama, relokasi mandiri – masyarakat mencari sendiri lokasi pindah, kemudian pemerintah pusat membangun rumah di lokasi tersebut; kedua, relokasi terpusat – lokasi relokasi disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah; dan ketiga, tetap tinggal di tempat asal – namun rumah ditinggikan bagi mereka yang enggan pindah dari tanah kelahirannya.

Di samping itu, pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tiga sumber utama masalah banjir, yakni pendangkalan danau, sedimentasi sungai, dan pengelolaan sampah. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum penataan Danau Tondano agar lebih lestari ke depan.
Meski relokasi terdengar logis secara teknis, implementasinya perlu mempertimbangkan aspek sosial-budaya. Tidak mudah meminta masyarakat meninggalkan tanah warisan leluhur mereka di sekitar danau. Selain faktor emosional tersebut, relokasi juga berisiko menimbulkan dampak sosial-ekonomi apabila tidak dipersiapkan dengan cermat. Warga yang dipindahkan rentan kehilangan sumber penghidupan lamanya; relokasi yang tidak matang justru bisa mengakibatkan hilangnya pemasukan dan meningkatnya pengangguran di kalangan mereka.
Opsi ketiga (tetap tinggal dengan rumah ditinggikan) muncul karena kenyataan itu – banyak warga Tondano yang secara emosional terikat dengan tanah kelahirannya. Pemerintah menyadari hal ini sehingga menekankan pentingnya solusi yang adil bagi masyarakat terdampak.
“Semuanya akan ditata sesuai regulasi Kementerian PUPR dan RDTR yang berlaku,” ujar Camat Remboken, Vecky Sengke, seraya mengakui bahwa prosesnya tentu butuh waktu dan dukungan warga.
Selain relokasi, dirancang pula “grand design” restorasi Danau Tondano yang komprehensif. Pemerintah pusat mencanangkan keterlibatan multi-pihak – pemerintah daerah, komunitas masyarakat, pihak swasta, hingga akademisi – dalam satu rencana induk pemulihan danau. Penguatan tata kelola terpadu menjadi kunci, termasuk penegakan tegas regulasi zonasi sempadan yang selama ini diabaikan. Penataan ulang sempadan dengan solusi yang tidak merugikan masyarakat (misalnya memberi ganti untung bagi pemilik lahan di garis sempadan, atau merelokasi dengan kompensasi layak) akan menjadi bagian dari grand design ini.
Pengembangan ekowisata berkelanjutan turut digadang sebagai salah satu pilar restorasi Danau Tondano. Keindahan alam Tondano yang dikelilingi Gunung Kaweng, Bukit Tampusu, Pegunungan Lembean, dan Gunung Masarang, ditambah kekayaan budaya lokal (seperti legenda asal-usul danau dan situs sejarah Benteng Moraya), berpotensi besar menarik wisatawan. Dengan pengelolaan tepat, ekowisata dapat mendukung konservasi sambil menggerakkan ekonomi rakyat di sekitar danau.
Pemerintah Kabupaten Minahasa telah mencanangkan beberapa event pariwisata berbasis danau dan mendorong investasi ramah lingkungan di sektor ini. Harapannya, danau yang sehat kelak tak hanya aman dari banjir, tapi juga menjadi sumber mata pencaharian baru yang hijau bagi warga setempat.

Bagi sebagian warga, rencana pemulihan pemerintah tersebut haruslah berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Noldy, warga Tuutu, menyarankan pemerintah mengembangkan program pemanfaatan eceng gondok yang bisa menjadi peluang kerja bagi warga yang kehilangan mata pencaharian. Menurutnya, eceng gondok yang melimpah seharusnya bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi – misalnya kerajinan atau pupuk kompos – daripada sekadar dibuang.
“Saya memilih pemerintah (saat Pemilu), tapi rasanya pemerintah tidak peduli dengan orang-orang yang sudah memilih mereka,” keluh Noldy, menggambarkan kekecewaan warga yang merasa jerih payahnya belum dihargai. Keluhan ini merujuk pada program padat karya eceng gondok sebelumnya yang upahnya sangat rendah. Jika pemerintah serius, ia berharap ada pelatihan dan modal usaha agar masyarakat bisa mengubah tanaman pengganggu itu menjadi berkah ekonomi.
Para aktivis lingkungan tak kalah sigap menawarkan solusi. Denny Taroreh adalah salah satu yang konsisten bersuara. Ia telah dua kali mempresentasikan konsep pemanfaatan eceng gondok menjadi eco-enzim di hadapan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I. Alih-alih hanya membasmi eceng gondok, Denny justru mengusulkan memanfaatkan gulma itu sebagai bahan baku perbaikan kualitas air danau.
“Tanaman ini dapat diolah menjadi eco-enzim yang berfungsi mereduksi polutan,” jelasnya. Eco-enzim adalah cairan hasil fermentasi limbah organik (termasuk tumbuhan air) yang mengandung senyawa kimia aktif untuk menetralisir polusi. Denny memaparkan bahwa eceng gondok bisa difermentasi minimal tiga bulan hingga menghasilkan cairan eco-enzim.
“Cairan ini dapat menyehatkan badan air, termasuk danau yang sudah tercemar berat seperti Danau Tondano. Singkatnya, eco-enzim bisa membuat air yang ‘sakit’ jadi normal atau bahkan lebih sehat, karena mampu mengurangi kandungan polutan. Namun aplikasinya tidak cukup sekali; harus berulang dan berkelanjutan,” papar Denny Taroreh.
Ia menekankan, memulihkan Danau Tondano yang begitu luas tentu tidak semudah menyehatkan kolam ikan 5×5 meter – butuh upaya masif dan berkelanjutan. Gagasan eco-enzim ini sempat ditolak kepala BWS sebelumnya, namun ketika Denny presentasikan ulang kepada kepala BWS yang baru (Ir. Sugeng, M.T.), idenya dapat diterima karena sang kepala memahami konsepnya. Bahkan, Denny dan tim sudah melakukan uji coba metode serupa pada pengolahan alga di Danau Sineleyan, Tomohon, dan terbukti berhasil.
Sayangnya, meski sempat dibahas kembali di awal 2024, program eco-enzim Danau Tondano belum berjalan karena alasan keterbatasan anggaran dan pertimbangan efisiensi. Presentasi terakhir Denny ke pemerintah soal eco-enzim dilakukan Oktober 2024, namun hingga pertengahan 2025 tindak lanjut konkret belum tampak.
Selain eco-enzim, Denny juga menyoroti perlunya kebijakan yang konsisten dalam penanganan Danau Tondano. Menurutnya, selama ini upaya penyelamatan danau terkesan parsial dan sporadis, sehingga tidak memberikan hasil yang siginifikan.
“Pandangan dan tujuan semua pihak harus sama,” tegas Denny. Ia mengkritik setiap pergantian pemerintahan – baik di level kabupaten, provinsi, maupun pusat – yang cenderung membawa kebijakan baru tanpa kesinambungan dengan program sebelumnya.
“Setiap ada pergantian pemerintahan, upaya penanganan tidak berkesinambungan. Akibatnya, masalah selalu kembali seperti semula, bahkan baru ramai dibicarakan setelah terjadi banjir,” ujarnya.
Denny mempertanyakan, apakah akar persoalan Danau Tondano sebenarnya pendangkalan danau atau justru volume air berlebih? Jika masalah utamanya pendangkalan, maka solusi seperti relokasi warga hanyalah memindahkan masalah, bukan menyelesaikan sebab-musababnya. Ia menilai penanganan selama ini kurang fokus ke akar masalah.
Kompleksitas juga diperparah banyaknya instansi terlibat namun berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi utuh. Padahal, imbuhnya, sejak era Presiden Joko Widodo, Danau Tondano sudah ditetapkan sebagai danau prioritas nasional untuk diselamatkan. Namun hingga kini kolaborasi antara PLN, BWS, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat belum menemukan titik terang solusi. Masyarakat pun, lanjut Denny, cenderung apatis karena lelah dengan janji-janji kosong.
“Masalah ini sebenarnya bisa diatasi jika ada keseriusan dan kesamaan langkah dari semua pihak,” ujarnya optimis, mendorong kolaborasi yang nyata dari berbagai pihak.

* * *
Kisah tentang Noldy dan Linda Tumampas yang tetap bersuara dan berharap pada pemerintah, meski sering merasa diabaikan, menunjukkan semangat juang masyarakat sekitar Danau Tondano. Stevi Badu yang lantang menyerukan perlunya pengerukan dan mengajak perubahan perilaku warga dalam membuang sampah adalah contoh individu yang menjadi motor penggerak kesadaran lingkungan.
Jika program pengelolaan eceng gondok dapat dijalankan dengan lebih adil dan melibatkan masyarakat secara proporsional, hal ini bisa menjadi model pemberdayaan ekonomi yang sukses – mengubah masalah lingkungan menjadi sumber pendapatan, sekaligus menginspirasi komunitas lain.
Masa depan Danau Tondano ada di tangan kita bersama. Pemulihannya adalah tanggung jawab kolektif, yang membutuhkan tidak hanya intervensi struktural dan kebijakan yang kuat, tetapi juga perubahan perilaku, peningkatan kesadaran, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan upaya terpadu dan berkelanjutan, Danau Tondano dapat pulih dan kembali memberi manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi generasi mendatang.
Bagi orang Tondano, danau “orang-air” ini pernah menjadi berkah bagi leluhur Minahasa – dan dengan komitmen bersama, ia masih bisa diselamatkan agar tetap menjadi berkah untuk anak-cucu di masa depan. Bagi warga yang telah turun-temurun hidup di tepian Danau Tondano tentu berharap tak harus meninggalkan tanah kelarihannya. Mereka memilih bertahan sambil menggantungkan harapan pada upaya kolaboratif semua pihak – pemerintah, komunitas, dan para ahli – untuk memulihkan danau kebanggaan mereka. Di tengah terpaan bencana yang berulang, masyarakat Tondano terus merajut asa agar Danau Tondano kembali menjadi berkah yang memberi kehidupan, alih-alih ancaman yang membawa bencana.***
Liputan ini dibiayai dari dukungan program Jurnalisme Aman oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara.
Indra Umbola, ikut berpartisipasi dalam liputan ini.